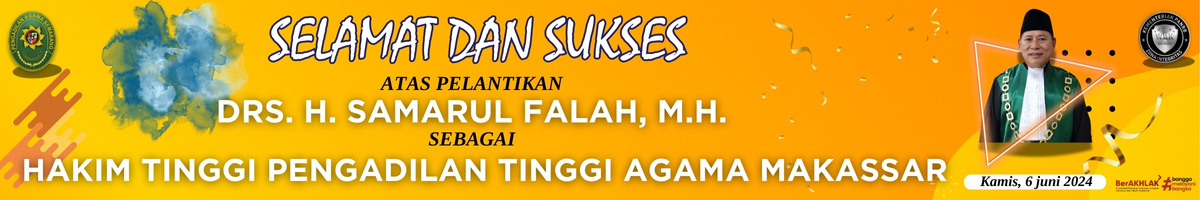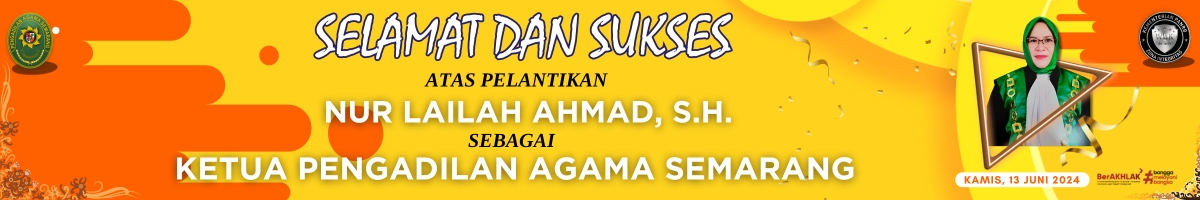Perempuan dan Label ‘Kaum Rentan‘: Refleksi atas Paradoks Kesetaraan
Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)
"Perempuan dan Label Kaum Rentan: Refleksi atas Paradoks Kesetaraan"
Dalam banyak forum kebijakan, perempuan kerap disebut sebagai bagian dari kaum rentan. Di antara kategori lain seperti anak-anak, disabilitas, lansia, atau masyarakat adat, perempuan sering menempati daftar teratas kelompok yang "harus dilindungi". Tapi timbul pertanyaan: apakah semua perempuan memang selalu rentan? Apakah laki-laki tidak mungkin termasuk kaum rentan? Dan yang lebih penting, apakah pelabelan ini tidak justru bertentangan dengan semangat kesetaraan gender yang diperjuangkan selama ini?
Secara umum, kaum rentan adalah kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah secara sosial, ekonomi, atau hukum, sehingga lebih mudah mengalami pelanggaran hak dan kesulitan mengakses keadilan. Dalam banyak realitas, perempuan memang masih menghadapi kekerasan berbasis gender, diskriminasi di dunia kerja, pengabaian hak kesehatan reproduksi, dan ketimpangan akses pendidikan—khususnya di wilayah pedesaan atau komunitas marginal. Maka wajar jika dalam konteks ini, perempuan masuk dalam kategori rentan.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa kerentanan bukanlah sifat kodrati. Ia bukan bawaan jenis kelamin, tetapi lebih merupakan hasil dari konstruksi sosial dan relasi kuasa yang timpang. Perempuan disebut rentan karena sistem dan budaya yang masih patriarkis, bukan karena dirinya lemah. Di sisi lain, laki-laki pun bisa menjadi kaum rentan jika berada dalam kondisi serupa: miskin, penyandang disabilitas, korban kekerasan rumah tangga, pekerja informal yang tidak dilindungi hukum, atau hidup dalam konflik.
Label “perempuan sebagai kaum rentan” bisa menjadi problematis jika digunakan secara sembarangan. Ia bisa berubah menjadi stigma yang justru melemahkan posisi perempuan, seolah-olah mereka selalu dalam posisi pasif yang menunggu perlindungan, bukan sebagai subjek aktif yang berdaya dan menentukan arah hidupnya sendiri. Ini tentu bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak, potensi, dan tanggung jawab yang setara dalam kehidupan sosial.
Padahal, sejarah dan kenyataan menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya korban, tetapi juga pejuang. Mereka memimpin gerakan sosial, menopang ekonomi keluarga, menjadi pendidik utama anak-anak bangsa, bahkan memegang peran strategis dalam politik dan pemerintahan. Kita bisa melihat sosok-sosok seperti Cut Nyak Dien, Kartini, hingga perempuan-perempuan di akar rumput yang memimpin komunitasnya dengan gagah berani.
Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat kerentanan secara interseksional, yaitu memahami bahwa faktor-faktor seperti kelas sosial, pendidikan, geografi, disabilitas, dan usia saling beririsan dan mempengaruhi kerentanan seseorang. Seorang perempuan kaya di kota besar tentu tidak berada dalam posisi yang sama dengan perempuan miskin di pelosok desa. Sama halnya, seorang laki-laki penyandang disabilitas tanpa akses layanan sosial pun bisa lebih rentan daripada perempuan sehat dari kelas menengah.
Kesetaraan gender tidak berarti menafikan kebutuhan perlindungan bagi perempuan dalam konteks tertentu. Justru, kesetaraan berarti memastikan setiap orang—terlepas dari jenis kelaminnya—mendapat akses, perlakuan, dan keadilan sesuai kondisi nyatanya. Bukan dengan menyamaratakan, tetapi dengan memperlakukan secara adil dan kontekstual.
Oleh karena itu, pelabelan perempuan sebagai kaum rentan sebaiknya digunakan secara hati-hati, proporsional, dan dengan kesadaran kritis. Tujuannya bukan untuk menstigma, tetapi sebagai pengingat bahwa perjuangan menuju masyarakat yang setara masih panjang, dan bahwa perlindungan harus beriringan dengan pemberdayaan. Perempuan bukan objek kasihan, tetapi subjek perubahan.
Biodata Penulis
Nama: H.Asmu'i Syarkowi;
Lahir di Banyuwangi, 15 Oktober 1962;
Alumni UIN Sunan Kalijaga tahun 1988 (S-1), UMI Makassar tahun 2001 (S-2)